Mengapa Cancel Culture Kian Marak di Dunia Maya?
Bagus - Tuesday, 11 November 2025 | 02:00 PM


Pernah nggak sih kita lagi asyik scroll timeline media sosial, tiba-tiba muncul satu nama yang lagi ramai banget diomongin? Bukan karena prestasinya, tapi karena "ulah"-nya yang dianggap nggak pantas. Dari artis papan atas sampai influencer baru seumur jagung, nggak sedikit yang mendadak jadi sasaran empuk hujatan massal. Dalam sekejap, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa rontok seketika. Nah, fenomena ini, yang kita kenal sebagai 'cancel culture', belakangan memang lagi nge-trend banget di jagat maya. Ibaratnya, media sosial ini sudah jadi mahkamah rakyat yang putusannya bisa bikin pusing tujuh keliling.
Dulu, kalau ada selebriti bikin ulah atau perusahaan melakukan kesalahan, palingan cuma jadi gosip di koran atau obrolan bisik-bisik. Respon publiknya nggak secepat dan segamblang sekarang. Tapi ya gitu deh, namanya juga era digital, semua serba cepat dan transparan. Nggak ada lagi ruang buat 'ngumpet' ketika jari-jari netizen sudah mulai bergerak. Sebuah postingan lama yang 'nggak banget', ucapan yang nggak sensitif, atau bahkan perilaku di masa lalu, bisa tiba-tiba muncul ke permukaan dan memicu gelombang kemarahan yang nggak kaleng-kaleng.
Apa Itu Cancel Culture dan Kenapa Bisa Meledak?
Secara sederhana, cancel culture ini bisa diartikan sebagai bentuk boikot massal terhadap individu atau organisasi yang dianggap melakukan kesalahan moral, etika, atau sosial. Tujuannya? Tentu saja untuk 'membatalkan' atau 'mengenyahkan' mereka dari panggung publik, baik itu lewat pemutusan kontrak kerja, kehilangan endorse, atau sekadar dicerca habis-habisan sampai akun media sosialnya kena report massal. Yang bikin fenomena ini meledak di era sekarang adalah kekuatan media sosial. Platform seperti Twitter, Instagram, TikTok, dan Facebook memberikan ruang bagi siapa saja untuk menyuarakan pendapat, protes, bahkan amarah mereka secara instan dan masif.
Coba deh bayangkan, satu postingan kontroversial bisa langsung di-share ribuan kali dalam hitungan menit. Hashtag yang terkait dengan isu tersebut mendadak jadi trending topic. Para netizen ini kadang mirip detektif swasta, mereka mencari 'bukti' lain, mengorek-ngorek masa lalu si target, sampai akhirnya terkumpul 'dosa-dosa' yang lebih banyak. Prosesnya cepat, impersonal, dan seringkali nggak memberi ruang klarifikasi yang seimbang. Alhasil, opini publik pun cepat terbentuk dan susah dibendung. Kadang, rasanya seperti sedang menonton sinetron dengan plot twist yang bikin geleng-geleng kepala.
Pedang Bermata Dua: Kebaikan dan Keburukan Cancel Culture
Seperti pedang bermata dua, cancel culture ini punya sisi baik dan buruknya. Di satu sisi, ia bisa jadi alat yang powerful untuk meminta pertanggungjawaban dari mereka yang punya kuasa tapi bertindak semena-mena. Contohnya, kasus-kasus pelecehan seksual yang terbongkar setelah korban berani bersuara di media sosial, atau perusahaan yang dipaksa mengubah kebijakan diskriminatif karena tekanan netizen. Ini adalah bentuk kekuatan kolektif yang patut diacungi jempol, di mana suara-suara minoritas atau yang terpinggirkan bisa mendapatkan platform untuk didengar.
Tapi di sisi lain, nggak jarang juga cancel culture jadi boomerang atau malah jadi ajang main hakim sendiri. Ada beberapa poin yang bikin miris:
- Minimnya Proses Due Diligence: Seringkali, "vonis" sudah dijatuhkan sebelum ada pemeriksaan fakta yang menyeluruh. Informasi yang setengah-setengah atau sekadar rumor bisa jadi bahan bakar utama untuk memicu amarah.
- Hukuman yang Tidak Proporsional: Kesalahan kecil atau salah paham bisa berujung pada hilangnya karier dan reputasi seseorang secara permanen. Ibaratnya, melakukan kesalahan menjatuhkan mangkok, tapi hukumannya dipaksa jadi gelandangan. Sadis, kan?
- Ancaman untuk Kebebasan Berpendapat: Karena takut dicancel, banyak orang jadi enggan menyuarakan opini yang berbeda atau terkesan 'berani' di media sosial. Akhirnya, yang muncul di publik hanya opini-opini yang 'aman' atau sesuai arus mayoritas. Ini bisa menghambat diskusi yang sehat dan beragam.
- Mental Health yang Terkoyak: Bayangkan jadi target hujatan ribuan orang yang nggak kenal kamu sama sekali. Dampaknya pada kesehatan mental bisa sangat serius, mulai dari depresi, kecemasan, hingga keinginan untuk mengakhiri hidup.
- Kesulitan untuk Bertobat atau Memperbaiki Diri: Sekali dicap 'rusak', susah sekali bagi seseorang untuk mendapatkan kesempatan kedua. Padahal, manusia kan tempatnya salah dan khilaf. Bagaimana jika mereka sudah benar-benar menyesal dan ingin berubah?
Mencari Titik Tengah di Tengah Riuhnya Jagat Maya
Jadi, gimana dong kita menyikapi fenomena cancel culture ini? Apakah kita harus ikut-ikutan jadi hakim virtual, atau diam saja? Mungkin, kuncinya ada pada 'titik tengah' dan penggunaan akal sehat.
Pertama, penting bagi kita sebagai pengguna media sosial untuk punya filter. Jangan mudah terprovokasi atau ikut-ikutan menghujat tanpa tahu duduk perkaranya. Biasakan untuk mencari informasi dari berbagai sumber, cek fakta, dan jangan hanya menelan mentah-mentah apa yang lagi viral. Pikirkan juga, apakah kesalahan yang dilakukan benar-benar sefatal itu sehingga pantas "dibakar" di depan umum?
Kedua, mari kita bedakan antara meminta pertanggungjawaban (accountability) dengan persekusi massal (mob mentality). Meminta seseorang bertanggung jawab atas kesalahannya itu penting, terutama jika melibatkan isu serius seperti diskriminasi, pelecehan, atau penyalahgunaan kekuasaan. Tapi, ada batasnya antara kritik konstruktif dan hujatan membabi-buta yang didasari sentimen emosional belaka. Kalau sudah sampai ke titik doxing, ancaman fisik, atau bahkan menyasar keluarga si target, itu sudah melewati batas kemanusiaan.
Ketiga, mari kita sisakan ruang untuk empati dan kesempatan kedua. Manusia itu kompleks, dan kadang-kadang, kesalahan bisa jadi pelajaran berharga untuk tumbuh dan jadi pribadi yang lebih baik. Tentu saja, ini bukan berarti kita harus mentolerir semua kesalahan. Tapi, mungkin kita bisa mencoba memahami konteksnya, apakah ada niat jahat atau hanya ketidaktahuan? Apakah si pelaku sudah menunjukkan penyesalan dan keinginan untuk berubah?
Intinya, cancel culture adalah cerminan dari kekuatan sekaligus kerapuhan interaksi kita di media sosial. Ia bisa jadi alat keadilan yang efektif, tapi juga bisa jadi senjata berbahaya jika tidak digunakan dengan bijak. Semoga saja, kita semua bisa menjadi netizen yang lebih dewasa, kritis, dan berempati, sehingga media sosial kita tidak melulu dipenuhi drama dan kemarahan, tapi juga diskusi yang sehat dan konstruktif. Karena pada akhirnya, jari-jemari kita di keyboard itu punya kekuatan yang luar biasa, dan mari kita gunakan untuk hal-hal yang lebih baik.
Next News

Kecemasan Sosial di Era Komunikasi Virtual
7 days ago

Dampak Pendidikan Online pada Perkembangan Remaja: Antara Layar dan Realita yang Makin Jauh?
7 days ago

Pendidikan Seks di Indonesia: Antara Ada dan Tiada
7 days ago
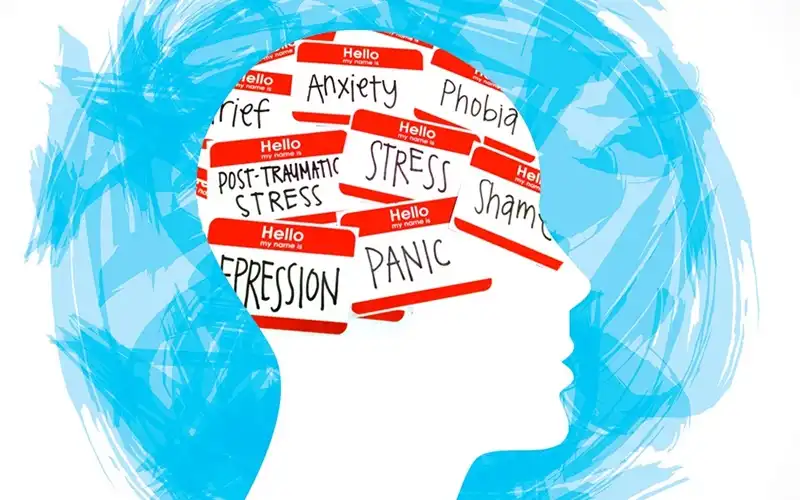
Mental Health: Bukan Mitos, Bukan Kurang Iman!
7 days ago

Generasi Z: Penjaga Tradisi di Era Digital?
7 days ago

Deru Mesin, Derasnya Hujan: Kisah Pak Budi, Pejuang Ojol yang Tak Kenal Menyerah di Bawah Langit Surabaya
7 days ago

Lawan Short Attention Span! Jauhi Medsos?
7 days ago

Ketika Scroll Jadi Diagnosis: Fenomena Self-Diagnose dari Media Sosial yang Ngeri-Ngeri Sedap
7 days ago

Kota Meluas, Hijau Menciut: Realita Pahit Generasi Kini
7 days ago

Terjebak Paradoks Digital: Koneksi Semu, Hati Hampa
7 days ago






