Ketika Scroll Jadi Diagnosis: Fenomena Self-Diagnose dari Media Sosial yang Ngeri-Ngeri Sedap
Bagus - Wednesday, 12 November 2025 | 02:00 PM


Pernah nggak sih lagi asyik scroll TikTok atau Instagram, eh tiba-tiba muncul video tentang gejala ADHD? Atau mungkin reels yang ngejelasin ciri-ciri anxiety disorder? Nggak sedikit dari kita yang langsung 'klik', merasa relate, terus mulai mikir, "Jangan-jangan ini gue banget, nih!" Nah, fenomena inilah yang makin menjamur belakangan ini: self-diagnose alias mendiagnosis diri sendiri cuma bermodalkan info dari media sosial. Dulu mungkin kita ke perpustakaan atau browsing di WebMD, sekarang? Cukup buka aplikasi, scroll, dan boom! Segudang 'diagnosis' siap menyapa. Sebenarnya, mencari informasi tentang kesehatan mental itu bagus. Kesadaran akan pentingnya kesehatan jiwa memang lagi naik daun, dan media sosial punya peran besar di situ. Tapi, kalau informasi yang tadinya cuma buat menambah wawasan, ujung-ujungnya malah bikin kita percaya diri buat nyantumin label 'depresi' atau 'bipolar' ke diri sendiri tanpa konsultasi ahli, itu sih namanya sudah kebablasan. Ini bukan lagi soal cari tahu, tapi sudah masuk ke wilayah 'sok tahu' yang bisa berakibat fatal.
Algoritma Bikin Kita Makin Kepincut
Kenapa sih media sosial jadi ladang subur buat self-diagnose? Jawabannya simpel: aksesibilitas dan relevansi. Sekarang ini, nyari info apa aja tinggal pencet. Nggak cuma itu, algoritma cerdas di balik layar aplikasi ini jago banget bikin kita betah. Kalau kita pernah nyari soal 'overthinking' sekali aja, dijamin deh, berpuluh-puluh video tentang anxiety, OCD, atau isu kesehatan mental lainnya bakal mejeng di feed kita. Seolah-olah mereka bilang, "Ini lho, konten yang kamu butuhkan!" Dan jujur aja, kadang kita merasa nyaman di sana. Menemukan banyak orang yang 'senasib' rasanya kayak nemu zona nyaman di tengah hiruk-pikuk kehidupan. Kita jadi nggak merasa sendirian dengan gejala-gejala aneh yang dirasa. Para kreator konten, dengan gaya bahasa yang kekinian dan visual yang menarik, sukses bikin informasi yang tadinya berat jadi gampang dicerna. Mereka sering kali membagikan pengalaman pribadi yang bikin kita berpikir, "Wah, dia aja bisa berjuang, berarti gue juga bisa." Niatnya sih baik, untuk saling mendukung, tapi kadang 'relate' ini bisa jadi pedang bermata dua.
Sisi Terang yang Kadang Bikin Silau
Fair-nya nih, nggak semua buruk kok. Media sosial juga punya peran positif dalam meningkatkan kesadaran tentang kesehatan mental. Dulu, ngomongin depresi atau cemas itu tabu banget, kesannya kayak aib atau aib keluarga. Sekarang? Banyak influencer atau kreator konten yang berani buka-bukaan soal perjuangan mereka. Ini bagus buat mendestigmatisasi. Banyak orang jadi 'ngeh', "Oh, ternyata gejala ini ada namanya dan bukan cuma gue doang yang ngalamin!" Ini bisa jadi titik awal yang baik, semacam alarm kecil yang bikin kita mikir, "Oke, mungkin gue perlu cari tahu lebih lanjut." Informasi di media sosial bisa menjadi jembatan awal bagi seseorang yang mungkin selama ini merasa sendiri dengan masalahnya, untuk akhirnya berani mencari bantuan profesional. Paling tidak, media sosial berhasil membuka mata banyak orang bahwa kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik, dan bukan cuma soal 'kurang iman' atau 'banyak pikiran' doang. Intinya, media sosial bisa jadi pintu gerbang untuk menyadari bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan.
Jebakan Batman: Ketika Self-Diagnose Jadi Bumerang
Tapi ya, seperti pepatah bilang, "Too much of anything is bad." Sisi gelap self-diagnose ini lebih banyak dan jauh lebih 'ngeri' dari yang kita kira. Yang paling kentara itu misinformasi. Bayangin, ada video singkat yang cuma 60 detik ngejelasin 'ciri-ciri bipolar' berdasarkan pengalaman pribadi kreatornya. Padahal, diagnosis bipolar itu butuh observasi panjang dan kompleks oleh profesional kesehatan mental, bukan cuma dari daftar ceklis yang disebarkan di internet. Gimana bisa kita menyimpulkan diri kita bipolar cuma dari video segitu? Ini kan sama aja kayak belajar bedah otak dari tutorial YouTube. Lalu, ada lagi fenomena 'oversimplification'. Kondisi mental yang rumit, dengan segudang nuansa dan spektrumnya, malah disederhanakan jadi poin-poin singkat yang gampang dicerna tapi menyesatkan. Contohnya, "Kalau kamu sering overthinking dan susah tidur, berarti kamu anxious." Padahal, overthinking dan susah tidur bisa jadi gejala dari banyak hal, dari stres biasa, masalah fisik, sampai kondisi medis lainnya. Ini bikin kita jadi paranoid. Dikit-dikit panik, "Jangan-jangan ini gue banget, nih!" Belum lagi soal 'confirmation bias'. Saat kita udah kepikiran satu diagnosis dari media sosial, kita cenderung mencari-cari bukti yang mendukung diagnosis itu pada diri kita sendiri. Gejala-gejala umum yang mungkin dialami banyak orang, tiba-tiba kita asosiasikan dengan penyakit 'serius'. Ujung-ujungnya? Tambah cemas, tambah puyeng, dan bukannya lega malah bikin mental makin amburadul. Kita jadi merasa serba salah, mau ngerasa senang dikit takut dibilang 'mania', mau sedih dikit takut dibilang 'depresi'. Yang lebih parah, ini bisa menunda kita untuk mencari bantuan profesional. Merasa sudah tahu 'penyakitnya', jadi malas ke psikolog atau psikiater, padahal diagnosis awal kita itu bisa jadi salah besar dan justru menghambat penanganan yang tepat. Padahal, penanganan yang terlambat bisa bikin kondisi makin parah dan waktu pemulihan jadi lebih lama.
Tren 'Aku Juga!' dan Bahaya Labelling Sembarangan
Di platform kayak TikTok, misalnya, fenomena ini makin gaspol. Satu video viral tentang ADHD, besoknya langsung muncul segambreng video 'POV: aku pas didiagnosis ADHD' atau 'Tanda-tanda kamu punya ADHD'. Semua berlomba-lomba merasa 'aku juga!'. Ini menciptakan semacam tren, di mana kondisi kesehatan mental yang serius justru jadi kayak 'aksesori' atau label gaul yang keren untuk dipakai. Padahal, label itu bukan main-main. Ketika semua orang mulai melabeli diri sendiri dengan kondisi tertentu, orang-orang yang memang benar-benar mengalaminya bisa jadi nggak dianggap serius. "Ah, paling cuma ikut-ikutan tren TikTok doang," begitu kira-kira stigma baru yang muncul. Ini berbahaya karena meremehkan perjuangan nyata para penyintas kondisi mental tersebut dan bisa menghambat mereka untuk mendapatkan empati dan dukungan yang memang layak mereka dapatkan. Labelling diri sendiri juga bisa membatasi potensi diri, seolah-olah kita terjebak dalam kotak diagnosis yang mungkin tidak tepat.
Antara Awareness dan Diagnosis: Ada Jurang yang Dalam
Penting banget buat kita semua untuk bisa membedakan antara 'awareness' (kesadaran) dan 'diagnosis'. Media sosial itu bagus buat awareness. Buat bikin kita melek bahwa ada isu-isu kesehatan mental di sekitar kita, dan bahwa gejala-gejala yang kita rasakan itu valid dan ada banyak orang lain yang merasakannya juga. Tapi, dari awareness ke diagnosis itu ada jurang yang dalam, dan jurang itu hanya bisa diseberangi oleh profesional yang berkompeten. Bayangin deh, kalau kamu batuk-batuk, terus cari info di Google, muncul gejala TBC, terus kamu langsung self-diagnose TBC. Padahal bisa jadi cuma flu biasa atau alergi. Sama halnya dengan kesehatan mental. Psikolog atau psikiater itu udah sekolah bertahun-tahun, punya pengalaman klinis, dan tools diagnostik yang komprehensif. Mereka nggak cuma melihat gejala di permukaan, tapi juga riwayat kesehatanmu, lingkunganmu, pola pikirmu, sampai potensi diagnosis banding lainnya. Ini proses yang kompleks, nggak bisa cuma modal video 60 detik atau thread Twitter yang cuma casing-nya doang.
Mendingan Mana? Ngobrol Sama Ahlinya, Dong!
Jadi, kalau kamu atau orang terdekatmu merasa punya gejala yang bikin nggak nyaman, yang udah mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, jangan ragu untuk cari bantuan profesional. Nggak perlu takut atau malu. Psikolog atau psikiater itu bukan cuma buat orang 'gila', tapi buat siapa aja yang butuh bantuan untuk memahami dan mengelola emosi serta kondisi mentalnya. Mereka bisa memberikan diagnosis yang akurat dan rencana perawatan yang personal, bukan template dari internet. Media sosial boleh jadi teman untuk mencari informasi awal, untuk merasa tidak sendiri, atau untuk belajar istilah-istilah baru di dunia kesehatan mental. Tapi, jangan sampai media sosial jadi satu-satunya dokter pribadumu. Jadikan ia sebagai pintu gerbang menuju pemahaman yang lebih baik, dan biarkan para ahli yang jadi pemandu utamamu. Kesehatan mental itu investasi jangka panjang, jangan sampai keliru cuma karena terlalu nyaman sama jari yang gesit scroll sana-sini. Intinya, hati-hati ya, bestie. Nggak semua yang viral itu benar, dan nggak semua yang 'relatable' itu berarti kamu 'punya' penyakitnya. Mendingan gaspol ke ahlinya daripada pusing sendiri bikin diagnosis yang belum tentu valid. Ingat, jaga kesehatan mental itu penting, dan diagnosa yang tepat adalah langkah awal dari penyembuhan yang efektif. Jangan sampai malah makin gelagapan gara-gara overthinking hasil self-diagnose di dunia maya.
Next News

Kecemasan Sosial di Era Komunikasi Virtual
7 days ago

Dampak Pendidikan Online pada Perkembangan Remaja: Antara Layar dan Realita yang Makin Jauh?
7 days ago

Pendidikan Seks di Indonesia: Antara Ada dan Tiada
7 days ago
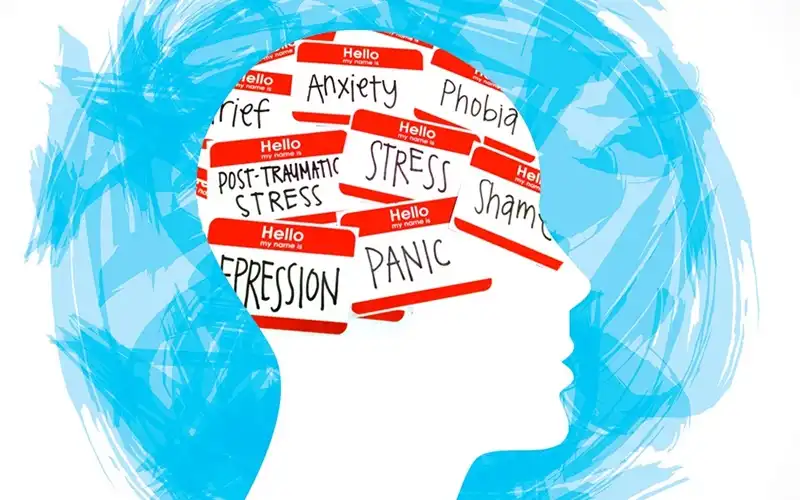
Mental Health: Bukan Mitos, Bukan Kurang Iman!
7 days ago

Generasi Z: Penjaga Tradisi di Era Digital?
7 days ago

Deru Mesin, Derasnya Hujan: Kisah Pak Budi, Pejuang Ojol yang Tak Kenal Menyerah di Bawah Langit Surabaya
7 days ago

Lawan Short Attention Span! Jauhi Medsos?
7 days ago

Kota Meluas, Hijau Menciut: Realita Pahit Generasi Kini
7 days ago

Terjebak Paradoks Digital: Koneksi Semu, Hati Hampa
7 days ago

Lagu Lama & Baju Y2K: Gelombang Nostalgia Menghantam!
7 days ago






